Jalan Terjal Upaya Perlindungan Perempuan
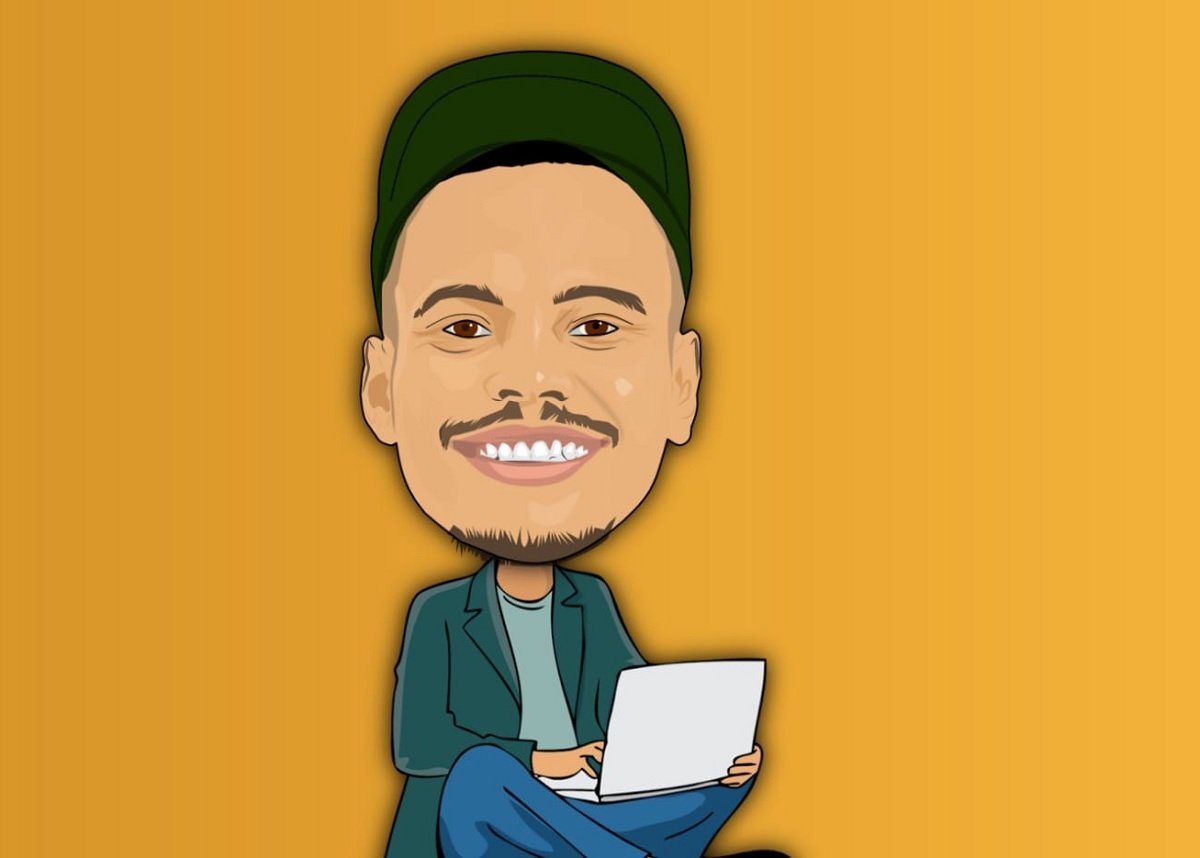
Oleh : Moh. Ridwan Litiloly (Aktivis dan Penggiat Demokrasi)
Willy Aditya Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah mengatakan draf RUU TPKS ditargetkan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI pada 15 Desember 2021 ini.
Pastinya pernyataan Willy menjadi kabar gembira bagi kaum-kaum hawa, terkususnya aktivis perempuan yang telah berjuang sedari dulu agar RUU tersebut dapat disahkan. Yaa, meskipun masi sebatas “kemungkinan” untuk bisa terjadi.
Upaya legalisasi payung hukum yang dinilai bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual memang selalu menghadapi jalan terjal.
RUU TPKS, yang dulunya masih bernama RUU PKS, sebenarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dari tahun 2016. Namun sayangnya dengan dalil pelegalan zina dan LGBT, pembahasan RUU PKS justru mengalami pertentangan oleh sebagian kelompok masyarakat, terutama yang berafiliasi dengan ormas keagamaan oposisi yang menyebabkan hingga saat ini RUU tersebut belum dapat disahkan.
Padahal, dengan kondisi yang saat ini, sebuah prodak hukum yang secara spesifik mengatur kekerasan seksual terhadap perempuan sanagat dibutuhkan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Kemudian jumlah total kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak hingga 3 juni di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.
Artinya, dengan peningkatan kasus yang begitu besar, dapat disimpulkan bahwa hanya dengan mengandalkan Undang-Undang seperti KUHP belum mampu membendung peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual dan melindungi para korbanya.
Dari sisi pendefenisian, KUHP dalam konteks kekerasan seksual hanya menyentuh pada perkosaan dan pencabulan saja. Berbeda dengan RUU TPKS yang membicarakan kekerasan seksual pada 9 jenis, yang diantaranya soal pelecehan seksual, memaksa perkawinan, memaksakan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.
Dengan begitu, jangkauan hukum RUU TPKS lebih luas dalam menjerat para predator-predator seksual yang sering lolos karena tidak ada yang memenuhi unsur legalitas sebagai tindakan pidana KUHP.
RUU TPKS ini kehadiranya begitu penting, karena selain melindungi para korban, dalam nomenklaturnya juga mengatur tentang rehabilitasi bagi para pelaku yang diatur dalam pasal 88 ayat 3.
Dengan sendirinya, kehadiran RUU ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku dari sisi hukum saja, melainkan ada upaya memperkecil angka kasusnya melalui perbaikan mental dan psikologi para pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya lagi.
Komitmen dan keseriusan pemerintah sebagai pembuat regulasi (regulatory) dalam melawan kekerasan seksual akan di uji melalui pengesahan RUU TPKS diakhir 2021 ini.
Jika masih tertunda dengan beragam argumentasinya seperti yang lalu-lau, Maka bisa disinyalir ada upaya pembiaran dari sekolompok orang agar masyarakat terkususnya perempuan-perempuan Indonesia tetap berada pada posisi ketidak pastian norma dan hukum atas perlindungan mereka.
Akan ada presepsi publik atas pebiaran kekososngan hukum dalam memberikan pencegahan, penanganan, hingga pemulihan terhadap kekerasaan seksual. Dengan begitu, perempuan Indonesia akan tetap berada dalam keadaan yang seperti dikatakan Emile Durkheim absence of social regulation normlessnee [tidak adanya norma-norma peraturan sosial].
Gagalnya Pembentukan Karakter
Selain kepastian legalisasi RUU TPKS, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi laboratorium pencetak sumber daya manusia dangan akhlak yang memerangi kejahatan kekerasan seksual, juga turut mengalami perjalanan yang terjal.
Seperti yang kita ketahui, para predator-predator kekerasan dan pelecehan seksual muncul dari berbagai latar belakangnya, baik itu pelakunya dari golongan tidak mampu, sampai kepada orang yang mapan hidupnya, pelaku yang terbatas pendidikanya hingga orang yang berpendidikan tinggi.
Ini artinya, keinginan melakukan hal tersebut tidak didasari oleh faktor ekonomi ataupun pendidikan, melainkan soal karakter dan kepribadian.
Berbicara soal karakter dan kepribadian, lembaga pendidikan formil pada tiap tingkatan (wajib belajar 9 tahun hingga perguruan tinggi) tentunya menjadi salah satu institusi yang paling bertanggungjawab.
Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional, dijelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.
Tentunya dengan tujuan agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kebperibadian, kecerdasan, ahklak mulia serta keterempilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Namun realitasnya tidak seperti tujuan suci dari UU tersebut. Dari data Komnas Perempuan, sepanjang 2015-2020 menunjukan dari keseluruhan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27 persen kasus terjadi di perguruan tinggi.
Data tersebut diperkuat dengan survei Koalisi Ruang Publik Aman pada 2019 yang menunjukan lingkungan sekolah dan kampus menduduki urutan ketiga lokasi terjadinya kekerasan seksual (15 persen), di bawah jalanan (33 persen) dan transportasi umum (19 persen).
Dari data dan angka tersebut, tentunya juga memerlukan evaluasi dan proyeksi kembali pada pengaplikasian kurikulum pembelajaran maupun sistem pendidikanya. Kurikulum pendidikan kita harus benar-benar bisa mengadopsi kebutuhan dan tantangan yang berkembang dalam masyarakat. Kurikulum yang orientasinya mengarah pada pembentukan karakter baik siswa maupun kepada tenaga pengajar atau dosenya.
Ini membutuhkan peran penting dari pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi negara tertinggi yang mengayomi dunia pendidikan. Apalagi Nadiem Makarim sebagai Mentrinya, dalam upaya mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo menciptakan Sumber Daya Manusi Unggul, telah menekankan dalam 5 visi besarnya di bidang pendidikan dengan memprioritaskan aspek pendidikan karakter sebagai point pertama.
Namun selama beberapa tahun pemerintahan ini berjalan, kita belum melihat hasil nyata dan capaian-capaianya menjauhkan dunia pendidikan dari serangan-serangan kekerasan seksualitas.
Sebenarnya jalan-jalan terjal ini bisa saja mudah dilalui asalkan ada kesadaran untuk menjadikan kasus kekerasan seksusal terhadap perempuan dan anak sebagai musuh bersama (common enemy).
Jika perdebatan terkait RUU TPKS ini hanya berkutat pada persoalan diksi dan narasi yang menimbulkan interpretasi lain, tentu itu hanya persoalan tehknis yang bisa diselesaikan dengan duduk bersama, bukan malah menunda dan membatalkan pembahasan.
Kemudian pada tataran dunia pendidikan, sistim beserta kurikulum pemebelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter dan moral peserta didik harus benar-benar terimplementasikan. Proses perekrutan para tenaga pengajar baik guru dan dosen harus melalui tahan yang memang selktif, dan hal ini juga seharusnya dibuat dalam aturan yang baku (*)
